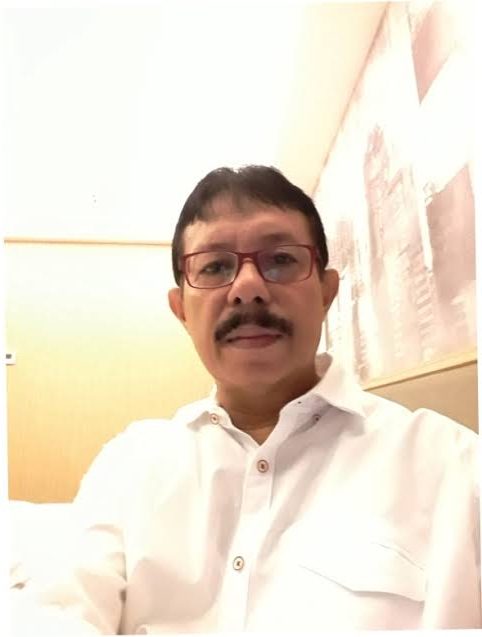Oleh: Amir Machmud NS
SEPERTI sudah kehabisan kata untuk mengungkapkan: bagaimanakah cara yang tepat untuk mengakhiri kekerasan terhadap wartawan? Demonstrasi menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja selama sepekan kemarin menyisakan ceritera yang sama dengan peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya. Setidak-tidaknya dari laporan berbagai media di Ibu Kota Jakarta dan di Surabaya, terdapat kejadian wartawan yang mengalami kekerasan dari aparat keamanan, yakni diintimidasi, peralatan kerja dirusak, produk jurnalistiknya dihancurkan, dan sebagainya.
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menegaskan, tindakan itu merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers, juga merusak sendi-sendi demokrasi. Pihaknya meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk mengusut tuntas dan segera melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang sudah menghambat, menghalangi tugas wartawan dengan merusak, merampas, dan menganiaya wartawan tersebut.
Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan empat sikap. Pertama, Polri wajib mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan personel kepolisian terhadap jurnalis dalam peliputan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja; serta menindaklanjuti pelaporan kasus serupa yang pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Kedua, mengimbau pimpinan redaksi untuk ikut memberikan pendampingan hukum kepada jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan aparat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Ketiga, mengimbau para jurnalis korban kekerasan maupun intimidasi aparat agar berani melaporkan kasusnya, serta memperkuat solidaritas sesama jurnalis. Keempat, mendesak Kapolri membebaskan jurnalis dan jurnalis pers mahasiswa yang ditahan.
Akar Persoalan
Dalam sejumlah insiden sebelumnya, penyelesaian kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan seperti tidak pernah menyentuh akar persoalan. Wartawan, medianya, atau organisasi profesi diminta untuk melapor ke Propam, dijanjikan ada proses hukum yang adil, atau ada kesepahaman untuk saling menghargai tugas masing-masing.
Wartawan, konon juga termasuk yang dilindungi ketika meliput unjuk rasa, diminta menunjukkan identitasnya. Akan tetapi, bagaimana jika kartu pengenal itu justru dibuang ketika dicoba untuk ditunjukkan, seperti yang menimpa wartawan CNNIndonesia.com di Jakarta?
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tegas mengamanatkan perlindungan terhadap wartawan ketika bertugas.
Ada sanksi hukum terhadap penghalang-halangan dalam mencari dan menyampaikan informasi. Akan tetapi bagaimana dengan realitas kejadian demi kejadian kekerasan yang menimpa wartawan? Muncul pula penjustifikasian tentang kondisi-kondisi tertentu di seputar demo, yang acapkali menyebabkan polisi melakukan kekerasan. Sebagaimana yang belum lama ini disampaikan oleh seorang anggota parlemen, seolah-olah wartawan harus bisa memahami keadaan-keadaan yang dihadapi polisi.
Apakah mengumpulkan fakta sebagai bahan-bahan informasi kemudian harus “menyesuaikan” hanya dengan apa yang disenangi dan dimaui oleh petugas keamanan? Apakah bila hal-hal yang dikumpulkan wartawan itu membuat mereka tidak nyaman, lalu menjadi pembenaran untuk boleh melakukan intimidasi?
Perspektif Pertama
Perspektif pertama yang dapat ditangkap dari kejadian yang terus berulang itu adalah kekhawatiran, betapa kekerasan terhadap wartawan bisa menjadi masalah laten yang kemudian “membudaya”, sehingga atas nama peraturan perundang-undangan apa pun tidak akan ada perlindungan yang mempan untuk menghentikan. Mengapa? Karena persoalannya berakar pada tradisi kekuasaan, pengedepanan psikologi kekuatan, dan sikap selalu memandang secara keliru terhadap pekerjaan wartawan.
Lalu bagaimana jalan keluar untuk mengubah pandangan seperti ini?
Undang-Undang Pers sudah banyak disosialisasikan ke kalangan penegak hukum, termasuk polisi. Tujuan untuk saling memahami tugas antara wartawan dengan aparat kepolisian diakomodasi dengan diskusi-diskusi, seminar, dan telaah bersama undang-undang ini.
Misalnya, Nota Kesepahaman Tahun 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan antara Kepolisian RI dengan Dewan Pers, secara substantif mengisyaratkan telah ada pemahaman yang cukup tentang Undang-Undang Pers.
Dengan fakta-fakta seringnya terjadi kekerasan terhadap wartawan, terbukalah kenyataan bahwa sosialisasi-sosialisasi, Mou, atau dialog-dialog yang telah pernah dilakukan di semua level akhirnya menjadi kurang bergaung, khususnya yang bersifat praktik perlindungan. Setidak-tidaknya, sangat mungkin MoU-MoU itu hanya dipahami di level pimpinan namun tidak sampai ke level lapangan.
Maka dengan cara bagaimana peran, fungsi, dan tugas wartawan itu seharusnya bisa dipahami oleh aparat?
Ketika regenerasi aparat yang bertugas di lapangan juga terus bergerak dari angkatan ke angkatan baru, bagaimana menjamin petugas di lapis terdepan itu bisa melanjutkan estafet pemahaman mengenai Undang-Undang Pers dan semua yang telah disepakati antara Polri dengan lembaga kewartawanan?
Artinya, konsistensi sosialisasi sebagai pembelajaran dan pemahaman yang tak kenal berhenti harus terus menerus dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan lembaga-lembaga kewartawanan. Termasuk memancarkannya secara teknis ke level-level terdepan.
Perspektif Kedua
Perspektif kedua ini lebih merupakan ajakan berintrospeksi. Ketika kekerasan fisik dan verbal terhadap wartawan terjadi, terkadang saya merenung: apakah penggunaan bahasa fisik itu tidak sampai menggugah hati nurani pihak yang melakukannya, dengan mengandaikan apabila hal itu menimpa dirinya sendiri?
Apakah mereka hanya akan menyederhanakannya sebagai sebuah risiko profesi, atau konsekuensi pekerjaan apa pun?
Bayangkanlah, bagaimana kalau kekerasan itu menimpa anak-anak mereka sendiri, orang tua mereka, atau kerabatnya? Bagaimana perasaan mereka kalau sampai terjadi cacat permanen, atau bahkan kondisi yang mengancam nyawa?
Tak terbetikkah di hati mereka bahwa yang dipukul, dipentung, atau ditendang itu adalah anak manusia, sesama makhluk Tuhan? Sebagai manusia beriman, tidakkah pelaku kekerasan itu berpikir tentang akhirat, mahkamah hari akhir yang pasti lebih adil dari kekerasan spontan yang mereka lakukan saat ini?
Ajakan berinstrospeksi ini bolehlah dipandang sebagai pilihan yang sudah mentok, ketika kita tidak lagi percaya untuk menunggu hadirnya kebenaran dari sebuah proses hukum. Dan, bukankah seharusnya tidak perlu ada rangkaian proses hukum manakala antarsesama anak manusia saling menghargai? Bukankah tidak harus terjadi kekerasan andai kita hidup dalam atmosfer welas asih: yang berkuasa tidak selalu unjuk kekuatan, dan rakyat benar-benar diayomi dengan limpahan payung kepemimpinan yang asih.
Kalau perspektif ini terabaikan, yakinilah kekerasan demi kekerasan akan terus terjadi, sebagai kondisi laten yang bisa muncul dalam setiap peristiwa; karena tak pernah ada kemauan untuk merenung, ber-muhasabah, dan mengulik nuraninya sendiri.
Persektif Ketiga
Perspektif ketiga mengenai jalan tengah menangani kekerasan terhadap wartawan adalah kemauan untuk melihat kepada diri sendiri secara objektif. Mari kita jangan menganggap diri paling benar, paling kuat, paling mampu menafsirkan hukum, dan janganlah merasa dengan kekuasaan berhak melakukan apa saja, terhadap siapa saja, dengan bahasa mereka sendiri.
Marilah berendah hati untuk merasa sebagai bagian dari elemen bangsa. Mari mengembangkan sikap tawaduk, karena bukankah manusia adalah makhluk Tuhan yang paling berintelejensia? Marilah pula berkemauan untuk menjadi penjaga dan perawat bangsa, dengan lebih memahkotakan harkat kemanusiaan kita.
Yakinilah, hidup akan menjadi lebih indah dengan kebersamaan, kesalingpemahaman, dan tidak mendominasi antara satu status terhadap status lainnya, antara satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya.
Apa untungnya pamer kekuasaan dan unjuk kekuatan yang hanya menerbitkan sakit, dendam, dan kebencian?
— Amir Machmud NS, wartawan SUARABARU.ID, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah